tUGAS HARI SABTU - Hallo sahabat Teknologi Terbaru, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul tUGAS HARI SABTU, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : tUGAS HARI SABTU
link : tUGAS HARI SABTU
tUGAS HARI SABTU
Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah situasi yang tidak
menguntungkan seperti saat ini, kebijakan pemberian sejumlah insentif
fiskal oleh pemerintah merupakan hal yang cukup positif.
Insentif fiskal ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terjaganya tingkat konsumsi dan investasi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi minimal bisa bertahan di kisaran 5,8%-6%.
Setidaknya, kebijakan seperti ini pernah ditempuh pemerintah pada 2009 dan dampaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%. Hanya Indonesia, China, dan India yang saat itu mampu tumbuh positif.
Apa yang dimaksud insentif fiskal? Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah insentif bea masuk dan bea keluar, insentif pajak, dan subsidi. Insentif fiskal dalam beberapa tahun terakhir gencar dilancarkan pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global.
Pada 2009, insentif fiskal diberikan sebesar Rp56,4 triliun untuk keringanan pajak dan kepabeanan serta Rp17 triliun untuk subsidi dan peningkatan belanja negara untuk dunia usaha. Insentif non fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik, seperti keamanan, lokasi, pelayanan, dan infrastruktur.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
Insentif fiskal ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi terjaganya tingkat konsumsi dan investasi yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi minimal bisa bertahan di kisaran 5,8%-6%.
Setidaknya, kebijakan seperti ini pernah ditempuh pemerintah pada 2009 dan dampaknya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9%. Hanya Indonesia, China, dan India yang saat itu mampu tumbuh positif.
Apa yang dimaksud insentif fiskal? Insentif fiskal adalah pemanfaatan pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Contohnya adalah insentif bea masuk dan bea keluar, insentif pajak, dan subsidi. Insentif fiskal dalam beberapa tahun terakhir gencar dilancarkan pemerintah untuk mengantisipasi krisis ekonomi global.
Pada 2009, insentif fiskal diberikan sebesar Rp56,4 triliun untuk keringanan pajak dan kepabeanan serta Rp17 triliun untuk subsidi dan peningkatan belanja negara untuk dunia usaha. Insentif non fiskal adalah insentif yang berbentuk fasilitas baik fisik maupun non fisik, seperti keamanan, lokasi, pelayanan, dan infrastruktur.
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.
regulasi/re·gu·la·si/ /régulasi/ n pengaturan;
-- hipotonik Bio 1
kemampuan menyesuaikan hidup bagi organisme yang hidup dalam air asin
dengan cara mempertahankan kandungan garam di dalam cairan tubuh agar
tetap lebih rendah daripada air; 2 kemampuan
menyesuaikan hidup yang terdapat pada hewan air tawar dengan cara
mempertahankan kandungan garam dalam cairan tubuh agar tetap lebih
tinggi daripada air di luar tubuh
Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan
keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau
distributor dalam suatu industri
untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi
merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau
hanya untuk mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.[1]
Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.[2] Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[1] Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.[2] Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI
Oleh :
Diat Sujatman
Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai ”power”/kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di perdesaan.
Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok.
Dalam aspek keorganisasian kelompoktani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompoktani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada.
Petani yang mandiri dan tangguh adalah hal yang diinginkan sejak dahulu. Keinginan tersebut yang menjadikan dasar bagi pengembangan suatu sistem pendidikan pertanian untuk petani yang lazim disebut penyuluhan pertanian. Dalam perjalanan waktu penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dapat mempertahankan kemurniannya sebagai mitra petani untuk mengembangkan kemampuan sesuai keinginan dan kesempatannya menuju kemandirian sebagai subjek.
Terdapat kesamaan pandangan dari beberapa teori yang mengemukakan tentang ciri pemberdayaan dalam menciptakan kemandirian kelompoktani. Dari beberapa teori yang dikemukakan tersebut, dapat kita ambil tiga ciri pemberdayaan yang membedakannya dengan penyuluhan, yaitu 1) Otoritas, 2) Kemandirian dan 3) Keswadayaan. Dalam pemebrdayaan masyarakat tani pelaku utama (petani) dan pelaku usaha diupayakan untuk mempunyai otoritas, kemandirian dan keswadayaan dalam menentukan jenis, volume dan sistem usahataninya serta kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang dibentuknya.
Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar kelompoktani yang ada sekarang telah dibentuk (bukan terbentuk) pada masa lalu dan menjadi warisan untuk para penyuluh pertanian pada masa sekarang. Hal ini menyebabkan masih banyak kelompok tani yang tingkat kemandiriannya rendah dan masih tergantung pada intervensi program pemerintah.
Dari beberapa teori kemandirian kelompoktani, terungkap bahwa kemandirian kelompoktani harus timbul dari keinginan kolompoktani itu sendiri. Penyuluh pertanian hanya membantu mendampingi dan menjadi fasilitator dalam proses kelompoktani tersebut menjadi mandiri.
Menurut Departemen Pertanian (2007), kelompoktani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompoktani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada.
Kenyataan di lapangan masih banyak penyuluhan pertanian melihat tugasnya sebagai orang yang meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan agar tujuan penyuluhan tercapai dengan memuaskan. Tetapi ada juga penyuluh pertanian yang menginginkan agar petani dapat mengambil keputusannya sendiri dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), dalam membuat keputusan secara mandiri, petani dalam suatu kelompok tani harus mengetahui alternatif yang digunakan dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Penyuluh pertanian dapat membantu petani pada tahap ini karena informasi demikian dapat diperoleh dari penelitian.
Kelompok dapat dikatakan mandiri dalam bidang usahanya jika mereka telah mampu mengelola usaha (baik perorangan maupun kelompok) yang efisien dan menguntungkan secara berkelanjutan serta ramah lingkungan (Deptan, 2007).
Kemandirian kelompok dapat ditelusuri paling tidak dari tingkat kemampuan usahanya untuk dikembangkan secara komersial guna mengatasi daya beli di perdesaan (Pranaji, 1994).
Menurut Tjokrowinoto (1991), kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk tetap eksis atas dasar segala keterbatasan yang menyertainya. Dalam kemandirian tercermin makna keberlanjutan (sustainable) dan memiliki kemampuan untuk menjaga sumber daya alam.
Kemandirian kelompoktani erat kaitannya dengan prinsip dasar penyuluhan pertanian. Menurut Valera et al (1987), prinsip penyuluhan pertanian adalah bekerja bersama sasaran (klien) bukan bekerja untuk sasaran. Sasaran penyuluhan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan dimulai dari apa yang diketahui dan dimiliki oleh sasaran. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan organisasi pembangunan lainnya. Selanjutnya, informasi yang disampaikan harus dua arah dan masyarakat harus ikut dalam semua aspek kegiatan pendidikan dan penyuluhan tersebut.
Peningkatan kemampuan kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri merupakan arah/tujuan dari pengembangan kelompoktani agar mampu memanfaatkan kesempatan, peluang dan iklim kondusif dalam menjalankan usahataninya.
Dalam hal kemandirian kelompoktani, mantan Menteri Pertanian Wardojo (1992) mengemukakan bahwa, sering diperlukan usaha khusus untuk membuat rakyat mau bertindak memanfaatkan kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya. Jika para petani dan keluarganya tersebut telah mau bertindak ke arah perbaikan kehidupan maka dapat dikatakan bahwa petani telah berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh manfaat bukan sekedar akibat dari adanya tekanan dari sistem sosial yang berlaku. Kemampuan petani dan keluarganya berpartisipasi dalam proses pembangunan didahului oleh suatu proses belajar untuk memperoleh dan memahami informasi, kemudian memprosesnya menjadi pengetahuan, melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Partisipasi dalam pembangunan tersebut mencakup partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.
Kemandirian kelompoktani adalah salah satu komponen yang mendasari penumbuhan kelompoktani dan erat kaitanya dengan pemberdayaan kelompoktani, kemandirikan kelompok tani adalah kunci utama suksesnya pembangunan pertanian. Dari ungkapan tersebut timbul pertanyaan, “ apakah penyuluh sebagai agen pembangunan pertanian dapat memandirikan kelompok tani ?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “Tidak”, karena yang dapat memandirikan kelompoktani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompoktani, dalam hal itu penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut :
1. Penguatan sumber daya kelompoktani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompoktani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompoktani, dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri.
2. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani.
3. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani
4. Menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani.
5. Mengembangkan pola kerja sama antara kelompoktani dengan kelompoktani lainnya dan antara kelompoktani dengan pihak lain.
Penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya. Petani belajar dengan mengerjakan sendiri, kepentingan petani diusahakan menjadi keinginan petani, petani dibantu agar dapat membantu diri sendiri dan dididik agar dapat mendidik diri sendiri.
Dalam perjalanan waktu penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak dapat mempertahankan kemurniannya. Pengembangan kemampuan petani sesuai keinginanya dan kesempatannya menuju kemandirian sebagai subjek menghadapai beberapa kenyataan yang bertolak belakang dari prinsip dan falsafah penyuluhan pertanian itu sendiri. Contoh kasus yang sering terjadi di lapangan adalah dimana petani dalam menerapkan paket-paket teknologi masih belum mandiri, masih tergantung pada pihak lain. Kenyataan menunjukan bahwa petani masih menunggu instruksi, melapor atau mengharapkan bantuan jika menghadapi persolan masih merupakan keadaan yang umum.
Adalah keadaan yang memprihatinkan bahwa penyuluh pertanian semakin ditafsirkan sebagai pemberi penerangan dibidang pertanian, sehingga terdengar anggapan bahwa setiap orang yang pandai bicara bisa menjadi penyuluh pertanian dengan menganjurkan ini dan itu.
Sikap terhadap para petani seperti yang disebutkan dalam contoh kasus diatas menimbulkan sikap petani mengenai dirinya sendiri sebagai sosok yang selalu mengharapkan dan patuh pada program-program, bantuan-bantuan dan pembinaan-pembinaan dari pemerintah. Hal demikian tersebut jauh dari harapan untuk membentuk petani sebagai subjek bukan sebagai objek dan mendorong kemandirian petani yang tangguh.
Kelompoktani hanya dapat dikembangkan oleh para petani sendiri. Upaya pemerintah untuk petani bagaimana mengorganisasikan dirinya seperti pengalaman masa lalu dengan Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) dan Organisasi Pelaksanaan Swasembada Beras (OPSSB), biasanya akan berakhir dengan kegagalan. Para penyuluh pertanian dapat mendorong petani untuk memikirkan cara terbaik dalam berorganisasi, contohnya dengan cara memberikan informasi keberhasilan organisasi petani atau kelompoktani di tempat lain.
Prinsip-prinsip penumbuhan kelompoktani didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut:
1) Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompoktani
2) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha
3) Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja kelompoktani)
4) Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri, para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian kelompoktani
5) Kesetaraan, artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar
6) Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling menumbuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh (Deptan, 2007).
Referensi
A.W. van den Ban dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: Kanisius
[DEPTAN] 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta: Deptan.
______. 2007. Sekolah Lapangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Modul Pelatihan Kelembagaan Usaha. Jakarta: Deptan.
______. 2007. Kegiatan Penyuluh yang Dikelola oleh Petani. Jakarta: Deptan.
______. 2009. Peratutran Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian Jakarta: Deptan.
______. 2009. Modul Diklat Alih Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Jakarta: Deptan.
Mardikanto T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Jakarta: Univ Pr.
Marzuki S. 2001. Pembinaan Kelompoktani . Jakarta: Universitas Terbuka.
Wiriaatmadja S. 1994. Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian. Jakarta: CV Yasaguna.
Zakaria A. 2000. Kelompok Tani Sebagai Basis Ketahanan Pangan. Laporan Pengkajian. Jakarta: Deptan
Yayasan Pengembangan Sinar Tani. 2001. Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani
Yayasan Pengembangan Sinar Tani. 2001. Membangun Pertanian Modern. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani
Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar.[2] Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E.McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik.[1] Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Beberapa negara sama sekali tidak mengenakan pajak, misalnya Uni Emirat Arab.[2] Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI
Oleh :
Diat Sujatman
Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian negara. Dengan peran tersebut maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai ”power”/kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di perdesaan.
Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat, umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu anggota kelompok.
Dalam aspek keorganisasian kelompoktani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompoktani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada.
Petani yang mandiri dan tangguh adalah hal yang diinginkan sejak dahulu. Keinginan tersebut yang menjadikan dasar bagi pengembangan suatu sistem pendidikan pertanian untuk petani yang lazim disebut penyuluhan pertanian. Dalam perjalanan waktu penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dapat mempertahankan kemurniannya sebagai mitra petani untuk mengembangkan kemampuan sesuai keinginan dan kesempatannya menuju kemandirian sebagai subjek.
Terdapat kesamaan pandangan dari beberapa teori yang mengemukakan tentang ciri pemberdayaan dalam menciptakan kemandirian kelompoktani. Dari beberapa teori yang dikemukakan tersebut, dapat kita ambil tiga ciri pemberdayaan yang membedakannya dengan penyuluhan, yaitu 1) Otoritas, 2) Kemandirian dan 3) Keswadayaan. Dalam pemebrdayaan masyarakat tani pelaku utama (petani) dan pelaku usaha diupayakan untuk mempunyai otoritas, kemandirian dan keswadayaan dalam menentukan jenis, volume dan sistem usahataninya serta kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang dibentuknya.
Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar kelompoktani yang ada sekarang telah dibentuk (bukan terbentuk) pada masa lalu dan menjadi warisan untuk para penyuluh pertanian pada masa sekarang. Hal ini menyebabkan masih banyak kelompok tani yang tingkat kemandiriannya rendah dan masih tergantung pada intervensi program pemerintah.
Dari beberapa teori kemandirian kelompoktani, terungkap bahwa kemandirian kelompoktani harus timbul dari keinginan kolompoktani itu sendiri. Penyuluh pertanian hanya membantu mendampingi dan menjadi fasilitator dalam proses kelompoktani tersebut menjadi mandiri.
Menurut Departemen Pertanian (2007), kelompoktani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani dan anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompoktani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada.
Kenyataan di lapangan masih banyak penyuluhan pertanian melihat tugasnya sebagai orang yang meningkatkan kemampuan petani dalam mengambil keputusan agar tujuan penyuluhan tercapai dengan memuaskan. Tetapi ada juga penyuluh pertanian yang menginginkan agar petani dapat mengambil keputusannya sendiri dalam rangka memperbaiki kehidupannya. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), dalam membuat keputusan secara mandiri, petani dalam suatu kelompok tani harus mengetahui alternatif yang digunakan dengan segala konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Penyuluh pertanian dapat membantu petani pada tahap ini karena informasi demikian dapat diperoleh dari penelitian.
Kelompok dapat dikatakan mandiri dalam bidang usahanya jika mereka telah mampu mengelola usaha (baik perorangan maupun kelompok) yang efisien dan menguntungkan secara berkelanjutan serta ramah lingkungan (Deptan, 2007).
Kemandirian kelompok dapat ditelusuri paling tidak dari tingkat kemampuan usahanya untuk dikembangkan secara komersial guna mengatasi daya beli di perdesaan (Pranaji, 1994).
Menurut Tjokrowinoto (1991), kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk tetap eksis atas dasar segala keterbatasan yang menyertainya. Dalam kemandirian tercermin makna keberlanjutan (sustainable) dan memiliki kemampuan untuk menjaga sumber daya alam.
Kemandirian kelompoktani erat kaitannya dengan prinsip dasar penyuluhan pertanian. Menurut Valera et al (1987), prinsip penyuluhan pertanian adalah bekerja bersama sasaran (klien) bukan bekerja untuk sasaran. Sasaran penyuluhan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dan dimulai dari apa yang diketahui dan dimiliki oleh sasaran. Dalam melaksanakan pekerjaan harus berkoordinasi dengan organisasi pembangunan lainnya. Selanjutnya, informasi yang disampaikan harus dua arah dan masyarakat harus ikut dalam semua aspek kegiatan pendidikan dan penyuluhan tersebut.
Peningkatan kemampuan kelompoktani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri merupakan arah/tujuan dari pengembangan kelompoktani agar mampu memanfaatkan kesempatan, peluang dan iklim kondusif dalam menjalankan usahataninya.
Dalam hal kemandirian kelompoktani, mantan Menteri Pertanian Wardojo (1992) mengemukakan bahwa, sering diperlukan usaha khusus untuk membuat rakyat mau bertindak memanfaatkan kesempatan dalam memperbaiki kehidupannya. Jika para petani dan keluarganya tersebut telah mau bertindak ke arah perbaikan kehidupan maka dapat dikatakan bahwa petani telah berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh manfaat bukan sekedar akibat dari adanya tekanan dari sistem sosial yang berlaku. Kemampuan petani dan keluarganya berpartisipasi dalam proses pembangunan didahului oleh suatu proses belajar untuk memperoleh dan memahami informasi, kemudian memprosesnya menjadi pengetahuan, melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Partisipasi dalam pembangunan tersebut mencakup partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.
Kemandirian kelompoktani adalah salah satu komponen yang mendasari penumbuhan kelompoktani dan erat kaitanya dengan pemberdayaan kelompoktani, kemandirikan kelompok tani adalah kunci utama suksesnya pembangunan pertanian. Dari ungkapan tersebut timbul pertanyaan, “ apakah penyuluh sebagai agen pembangunan pertanian dapat memandirikan kelompok tani ?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah “Tidak”, karena yang dapat memandirikan kelompoktani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompoktani, dalam hal itu penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra petani, pendamping dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut :
1. Penguatan sumber daya kelompoktani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompoktani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompoktani, dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri.
2. Pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani.
3. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani
4. Menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani.
5. Mengembangkan pola kerja sama antara kelompoktani dengan kelompoktani lainnya dan antara kelompoktani dengan pihak lain.
Penyuluhan pertanian diartikan sebagai sistem pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya. Petani belajar dengan mengerjakan sendiri, kepentingan petani diusahakan menjadi keinginan petani, petani dibantu agar dapat membantu diri sendiri dan dididik agar dapat mendidik diri sendiri.
Dalam perjalanan waktu penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak dapat mempertahankan kemurniannya. Pengembangan kemampuan petani sesuai keinginanya dan kesempatannya menuju kemandirian sebagai subjek menghadapai beberapa kenyataan yang bertolak belakang dari prinsip dan falsafah penyuluhan pertanian itu sendiri. Contoh kasus yang sering terjadi di lapangan adalah dimana petani dalam menerapkan paket-paket teknologi masih belum mandiri, masih tergantung pada pihak lain. Kenyataan menunjukan bahwa petani masih menunggu instruksi, melapor atau mengharapkan bantuan jika menghadapi persolan masih merupakan keadaan yang umum.
Adalah keadaan yang memprihatinkan bahwa penyuluh pertanian semakin ditafsirkan sebagai pemberi penerangan dibidang pertanian, sehingga terdengar anggapan bahwa setiap orang yang pandai bicara bisa menjadi penyuluh pertanian dengan menganjurkan ini dan itu.
Sikap terhadap para petani seperti yang disebutkan dalam contoh kasus diatas menimbulkan sikap petani mengenai dirinya sendiri sebagai sosok yang selalu mengharapkan dan patuh pada program-program, bantuan-bantuan dan pembinaan-pembinaan dari pemerintah. Hal demikian tersebut jauh dari harapan untuk membentuk petani sebagai subjek bukan sebagai objek dan mendorong kemandirian petani yang tangguh.
Kelompoktani hanya dapat dikembangkan oleh para petani sendiri. Upaya pemerintah untuk petani bagaimana mengorganisasikan dirinya seperti pengalaman masa lalu dengan Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) dan Organisasi Pelaksanaan Swasembada Beras (OPSSB), biasanya akan berakhir dengan kegagalan. Para penyuluh pertanian dapat mendorong petani untuk memikirkan cara terbaik dalam berorganisasi, contohnya dengan cara memberikan informasi keberhasilan organisasi petani atau kelompoktani di tempat lain.
Prinsip-prinsip penumbuhan kelompoktani didasarkan pada unsur-unsur sebagai berikut:
1) Kebebasan, artinya menghargai kepada para individu para petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompoktani yang mereka kehendaki sesuai dengan kepentingannya. Setiap individu bisa tanpa atau menjadi anggota satu atau lebih kelompoktani
2) Keterbukaan, artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha
3) Partisipatif, artinya semua anggota terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kinerja kelompoktani)
4) Keswadayaan, artinya mengembangkan kemampuan penggalian potensi diri sendiri, para anggota dalam penyediaan dana dan sarana serta pendayagunaan sumberdaya guna terwujudnya kemandirian kelompoktani
5) Kesetaraan, artinya hubungan antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar
6) Kemitraan, artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling menumbuhkan antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluh (Deptan, 2007).
Referensi
A.W. van den Ban dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: Kanisius
[DEPTAN] 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta: Deptan.
______. 2007. Sekolah Lapangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Modul Pelatihan Kelembagaan Usaha. Jakarta: Deptan.
______. 2007. Kegiatan Penyuluh yang Dikelola oleh Petani. Jakarta: Deptan.
______. 2009. Peratutran Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian Jakarta: Deptan.
______. 2009. Modul Diklat Alih Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Jakarta: Deptan.
Mardikanto T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Jakarta: Univ Pr.
Marzuki S. 2001. Pembinaan Kelompoktani . Jakarta: Universitas Terbuka.
Wiriaatmadja S. 1994. Pokok-Pokok Penyuluhan Pertanian. Jakarta: CV Yasaguna.
Zakaria A. 2000. Kelompok Tani Sebagai Basis Ketahanan Pangan. Laporan Pengkajian. Jakarta: Deptan
Yayasan Pengembangan Sinar Tani. 2001. Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani
Yayasan Pengembangan Sinar Tani. 2001. Membangun Pertanian Modern. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani
Demikianlah Artikel tUGAS HARI SABTU
Sekianlah artikel tUGAS HARI SABTU kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
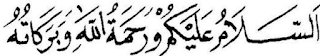

0 Response to "tUGAS HARI SABTU"
Post a Comment